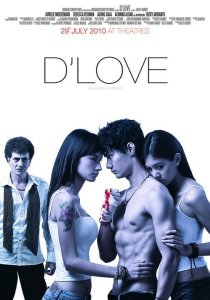Sama halnya seperti kisah-kisah Abu
Nawas dan Nasruddin yang termuat di berbagai literatur yang berasal
dari negeri Arab, Kabayan adalah sebuah tokoh imajinatif populer dari
Indonesia yang seringkali memuat dan menyindir mengenai bentuk tatanan
kehidupan masyarakat di kala itu pada setiap penceritaannya. Merupakan
tokoh yang berasal dari kisah-kisah masyarakat Sunda, Kabayan kemudian
menjadi sebuah tokoh ikonik bagi masyarakat Indonesia secara
keseluruhan setelah kisahnya sering dipopulerkan dalam bentuk buku
maupun dalam bentuk rilisan film layar lebar dan serial televisi.
Setelah terakhir kali diangkat dalam bentuk film pada Si Kabayan: Bukan Impian
(2000), kini karakter ikonik masyarakat Sunda tersebut kembali coba
diperkenalkan pada sebuah generasi baru yang berbeda lewat film karya
sutradara Guntur Soeharjanto (Otomatis Romantis, 2008), Kabayan Jadi Milyuner. Dengan naskah yang ditulis oleh Cassandra Massardi, kisah Kabayan Jadi Milyuner
sepertinya mencoba menggabungkan beberapa kisah Kabayan yang sebelumnya
telah pernah dihadirkan di layar lebar, mulai dari kisah perkenalannya
dengan wanita yang kelak akan menjadi jodohnya, Iteung, hingga
memasukkan sedikit kisah ‘berbau mistis’ mengenai jin yang ia miliki,
yang sebelumnya merupakan garis cerita utama pada kisah Si Kabayan dan Anak Jin
(1991). Bedanya, kisah Kabayan kini memiliki latar belakang cerita di
masa sekarang sekaligus menghadapkan keluguannya dengan perkembangan
zaman.
Diperankan oleh Jamie Aditya, Kabayan
kini dikisahkan harus menyelamatkan Pesantren As-Salam pimpinan Ustadz
Soleh (Slamet Rahardjo) yang kini sedang terancam keberadaannya akibat
niat seorang pengusaha real estate, Bos Rocky (Christian
Sugiono), yang ingin membeli tanah pesantren tersebut dan membangun
sebuah bangunan berfasilitas modern di sana. Jelas Rocky tidak akan
mendapatkan tanah tersebut dengan mudah. Kabayan serta teman baiknya,
Armasan (Amink), berhasil melakukan segala cara untuk dapat mencegah
mimpi Rocky untuk dapat menjadi nyata. Walau begitu, Rocky ternyata
masih menyimpan satu senjata rahasia yang sepertinya tidak akan dapat
ditolak oleh Kabayan dengan mudah.
Rahasia tersebut berwujud seorang wanita cantik bernama Iteung (Rianti Cartwright), akuntan Rocky yang berwajah bule
namun ternyata memiliki darah Sunda yang sangat kental. Mengetahui
kalau Kabayan diam-diam memendam rasa terhadap Iteung, Rocky kemudian
merayu Iteung agar mau untuk berpura-pura jatuh cinta kepada Kabayan
untuk kemudian membujuknya agar mau menandatangani surat pembelian
tanah. Dan rencana Rocky tersebut berhasil dengan mudah! Kini, tanah
pesantren telah berpindah kepemilikan dan sialnya, semenjak itu pula
Iteung tidak pernah lagi menunjukkan dirinya di hadapan Kabayan. Demi
mengejar rasa cintanya, sekaligus berusaha kembali untuk merebut tanah
pesantren, Kabayan bersama Armasan akhirnya nekat untuk pergi ke
Jakarta dan menemui Iteung.
Ada banyak hal yang sangat mengganggu dari Kabayan Jadi Milyuner,
khususnya pada naskah cerita film ini. Kisah cerita yang coba
dihadirkan terkesan seperti merupakan potongan-potongan kisah Kabayan
di film terdahulunya yang coba disatukan dalam deretan adegan film
untuk menjadi sebuah kesatuan jalan cerita. Tidak masalah jika sang
penulis naskah berhasil menyatukannya dengan menempatkan masing-masing
kisah tersebut secara teratur dan menyatu antara kisah yang satu dengan
yang lain. Sayangnya, kisah Kabayan Jadi Milyuner seringkali
terasa melompat antara adegan yang satu dengan adegan yang lain, dengan
bertambahnya durasi semakin membuat jalan cerita film ini semakin absurd dan tidak jelas kemana arah dan tujuannya. Dengan durasi film kira-kira sepanjang 100 menit, Kabayan Jadi Milyuner terasa seperti dipanjang-panjangkan dan berjalan sangat membosankan!
Beruntung, film ini memiliki Amink.
Komedian yang satu ini berhasil menjadi satu-satunya nilai plus yang
dapat diperoleh selama menyaksikan jalan cerita Kabayan Jadi Milyuner.
Beberapa kali, di saat yang penting pula, tingkah polah dan dialog
konyol yang dimiliki oleh Armasan, berhasil diterjemahkan dengan sangat
baik oleh Amink menjadi sebuah penampilan yang sangat menghibur.
Christian Sugiono juga sebenarnya tampil lumayan sebagai seorang tokoh
antagonis. Sayangnya, karakter yang ia mainkan kemudian harus terjebak
ke dalam penceritaan yang berusaha terlihat komikal namun justru sama
sekali tidak berhasil.
Jamie Aditya harus diakui mampu
membawakan karakter Kabayan dengan cara yang tidak buruk – Jamie
sendiri telah sering berperan sebagai Kabayan atau seorang yang
berdarah Sunda ketika ia masih menjadi VJ di MTV Indonesia. Namun,
ketika ia harus tampil berdampingan dengan Rianti Cartwright yang
berperan sebagai Iteung, sangat dapat dirasakan bahwa keduanya sama
sekali tidak memiliki chemistry yang pas. Hal ini menjadi
faktor besar mengapa film ini terasa sangat tidak dapat dinikmati
dengan baik ketika keduanya tampil di dalam jalan cerita. Sementara
talenta akting luar biasa dari duet aktor dan aktris senior, Didi Petet
dan Meriam Bellina, yang berpasangan sebagai Abah dan Ambu, harus
menyerah pada karakterisasi dangkal yang dituliskan untuk karakter
mereka. Walau begitu, lelucon terbesar dari Kabayan Jadi Milyuner adalah penampilan Melly Goeslaw, yang kali ini tidak hanya meneror penonton dengan lagu-lagu berlirik cheesy
yang dapat didengar di sepanjang film, namun juga terlihat menggelikan
dengan dandanan yang sama mengganggunya dengan kemampuan aktingnya di
film ini.
Dengan karakter yang telah sangat familiar dan jajaran pemeran yang sebenarnya cukup menjanjikan, Kabayan Jadi Milyuner
harus diakui terlihat seperti sebuah kesempatan besar yang terbuang
dengan percuma akibat buruknya jalan cerita yang dihadirkan. Naskah
yang dihadirkan benar-benar sangat tidak mampu untuk menghadirkan
sebuah tontonan yang dapat menghibur setiap penontonnya. Membosankan
dan dengan karakterisasi yang sangat dangkal. Ini yang kemudian
menjadikan jajaran pemeran film ini gagal memberikan permainan
terbaiknya, selain faktor miscast yang terasa terjadi pada beberapa karakter. Sebuah komedi yang sangat mengecewakan.
Rating: 2.5 / 5
Kabayan Jadi Milyuner (2010)
Directed by Guntur Soeharjanto Produced by Chand Parvez Servia Written by Cassandra Massardi Starring
Jamie Aditya, Rianti Cartwright, Amink, Christian Sugiono, Slamet
Rahardjo, Didi Petet, Meriam Bellina, Melly Goeslaw, Shogi Indra Dhuaja
Music by Anto Hoed & Melly Goeslaw Distributed by Starvision Running time 100 minutes Country Indonesia Language Indonesian